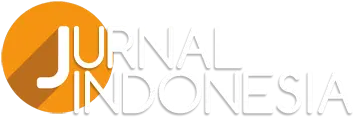Suatu ketika Bung Karno mengatakan, perempuan sendiri yang harus mengejar ketertinggalannya dari laki-laki, tetapi para laki-laki harus membantu upaya perempuan tersebut. Di buku Sarinah, Presiden RI pertama ini mengatakan, laki-laki tidak akan bisa maju tanpa mereka ikut membantu majukan pula para perempuan.
“Sikap BK ini menunjukkan bahwa BK pendukung affirmative policy agar muncul kekuatan yang setara antara laki-laki dan perempuan,” jelas Eva Kusuma Sundari, Politisi DPR RI asal Fraksi PDI Perjuangan.
BK menganalogikan dua sayap Burung Garuda sebagai sayap perempuan dan sayap laki. Keduanya harus sama kuat sehingga bisa terbang tinggi mengarungi angkasa.
Kuota perempuan dalam list pencalegan plus zipper system 3:1 oleh karenanya sah dalam pandangan BK karena memang statistik menunjukkan adanya gender gap di dunia politik. Demikian pula kebijakan afirmasi perempuan terkait kuota perempuan dalam kepengurusan inti parpol bisa dibenarkan karena sesuai Pancasila dan konstitusi RI 1945.
“Tetapi, apabila bicara keterwakilan perempuan di DPR maka pertanyaaanya adalah, apakah efektif sistem kuota di UU Pemilu kita? Tidak, karena hanya efektif untuk Pemilu 2004 yaitu mendongkrak dari 14 persen menjadi 18 persen,” jelas Eva lagi.
Di pemilu 2009 dan 2014, prosentasenya macet di seputar 18 persen. “Saya yakin di Pemilu 2019 juga hasilnya tidak akan berubah,” kata Eva.
Pancasila memang pro afirmasi tapi dalam prakteknya sistem pemilu kita kesusupan faham liberal yang mengharamkan hal tersebut. Kompetisi bebas (survival of the fittest) adalah sistem yang terbaik menurut denokrasi liberal karena affirmasi perempuan merusak ‘keadilan’ bagi pesaing laki-laki.
“Menurut faham liberal, ketimpangan gender lebih diakibatkan perempuan gagal berkompetisi,” tegas perempuan kelahiran Nganjuk, Jawa Timur ini.
Sedangkan menurut BK, lanjutnya, problem ketimpangan gender disebabkan dua sistem. Yaitu feodalisme yang mensubordinasi perempuan dan sistem kapitalisme yang eksploitatif terhadap perempuan (dan anak).
Sehingga, perempuan patut mendapat kompensasi atas nasib mereka sebagai korban melalui kebijakan afirmasi.
“Afirmasi adalah inheren dalam sistem demokrasi Pancasila. Kita mempunyai tradisi politik power sharing, melalui mekanisme musyawarah mufakat. Kita tidak mengenal ‘the winner takes all’ ala liberalisme yang amat ditentang BK, sehingga mengajukan demokrasi keterwakilan ala Indonesia yang disarikan dalam sila keempat dari Pancasila,” papar mantan konsultan di Asia Foundation periode 2003-2005 ini.
Jika esensi denokrasi adalah soal keterwakilan, kata Eva, maka kuota perempuan merupakan alat menjamin keterwakilan perempuan di DPR. Lalu, berapa persen ideal perempuan di DPR?
Eva yang menuntaskan S-2 Economics and Development Economics di Fakultas Ekonomi University of Nottingham, Inggris ini menjelaskan, Ketum Megawati pernah protes, mengapa critical number dibatasi 30 persen.
“Mengapa tidak sekalian 100 persen atau 50:50? Ini pemikiran progresif Ketum Megawati agar zipper system dinaikkan ke 50:50 seperti di Latin Amerika yang dalam waktu 10 tahun bisa meningkatkan partisipasi perempuan di parlemen secara signifikan,” kata Eva.
Logika yang sama, tambahnya, juga dipakai presiden Chile Michele Bachelet dan Presiden Argentina Cristina Elisabet Fernández de Kirchner dalam menyusun kabinet sehingga mainstreaming kesetaraan kesempatan bagi laki dan perempuan dilaksanakan serentak di eksekutif dan legislatif.
“Kebijakan affirmasi perempuan di Latin Amerika lebih progresif dan bersifat terobosan karena menggunakan jalur struktur kebijakan yang terlembaga (hukum), sedangkan di Skandinavia menggunakan jalur kultural yang dimotori parpol-parpol dan memakan waktu puluhan tahun untuk mengubah mental blok soal kesetaraan gender,” ujarnya.
Lebih jauh ia mengingatkan, satu lagi yang paling penting, yang merupakan necessary condition bagi efektifnya kebijakan afirmasi: sistem pemilu harus murah.
“Semua pendukung kebijakan afirmasi untuk kesetaraan gender seperti Skandinavia, Eropa Barat maupun Latin Amerika menggunakan sistem pemilu closed system yang ramah kepada siapapun termasuk perempuan, anak muda, penyandang disabilitas, buruh, maupun aktivis dan lain-lain,” tandas Eva,
Artinya, jika mau memperkuat Demokrasi Pancasila dari sisi keterwakilan, terutama the weak and the poor, agar DPR menjadi taman sari kelompok dan golongan, sistem pemilu harus kembali ke sistem tertutup.
Pileg sepatutnya kembali ke substansi yaitu kontestasi antar parpol bukan antar caleg seperti saat ini akibat sistem pemilu yang terbuka berakar pada Demokrasi Liberal.
Artinya, sistem pemilu liberal menegasikan afirmasi (kuota) karena keduanya kontradiktif dan itu sudah dibuktikan selama 3 pemilu persentase perempuan stagnan. Kedua, Sistem pemilu suara terbanyak menjauhkan kita dari cita-cita mewujudkan Demokrasi Pancasila yang mengutamakan keterwakilan berbagai kelompok kepentingan.
“Terutama kaum voiceless, sehingga keputusan politik Insyallah akan berdampak pada keadilan sosial di Indonesia,” pungkasnya. (hdl)