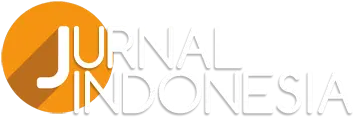Pakar bidang Antropologi FISIP UI, Achmad Fedyani Saifuddin menyampaikan kajiannya tentang pembangunan Papua dari perspektif sosial budaya dalam acara kunjungan studi mahasiswa Pascasarjana Universitas Cendrawasih di FISIP UI, akhir bulan lalu.
Pada kesempatan tersebut, Achmad berbicara tentang pandangan sosial budaya terhadap permasalahan dan pembangunan Papua dari waktu ke waktu.
Ia memaparkan bahwa Papua memiliki aneka ragam kebudayaan yang mencakup suku bangsa dengan teritorial, adat-istiadat, keyakinan, nilai-nilai, dan bahasa.
Pandangan etik yang telah berlangsung lama memandang masyarakat Papua dari sudut pandang orang luar, sehingga representasi Papua yang terlihat adalah homogenitas.
“Kira-kira tahun 70an, atau justru sebelumnya, Papua dilihat hanya sebagai satu provinsi besar. Jadi Papua sebesar itu hanya dipandang sebagai satu provinsi, Irian Jaya,” ucap Achmad Fedyani Saifuddin.
Selain homogenisasi, pelabelan gerakan-gerakan sosial budaya menjadi gerakan lokal terjadi dalam literatur-literatur yang dipublikasikan. Istilah-Istilah seperti Navistic movement, Revitalization Movement, Messianic Movement, atau Cargo Cult dipakai untuk melabel gerakan komunitas di Papua.
Pembingkaian yang serupa juga terjadi dari sudut pandang otoritas atau pemerintah. Gerakan-gerakan tersebut dipandang sebagai gerakan separatis, gerakan perlawanan yang kecenderungannya untuk memisahkan diri. Dalam hal ini, Achmad menekankan bagaimana vitalnya sebuah buku teks (textbook) membentuk pengetahuan generasi selanjutnya.
“Jadi, kajian-kajian Bapak Ibu sekalian yang sedang mengambil doktor, itu salah satu tempat yang sangat penting bagi kita untuk menyampaikan pesan-pesan yang terbaru. Meluruskan yang bengkok tadi,” ucapnya.
Masih dalam masa lampau, sudut pandang eksternal pun menganggap persoalan di Papua hanya menjadi persoalan domestik Indonesia. Kecenderungan negara-negara lain hanya mengamati dari jauh tanpa adanya keterlibatan.
Namun, perubahan masif dalam konteks informasi dan teknologi yang terjadi di dunia membuat aspek sosial budaya menjadi longgar (less bounded) dan lintas batas. Efeknya, masalah-masalah Papua tidak lagi menjadi urusan domestik Indonesia semata.
Banyak negara yang merasa masalah Papua adalah bagian dari masalah internasional dan global. Hal ini mendorong banyak negara merasa perlu terlibat dengan kepentingan tertentu.
“Kepentingannya ada di Papua. Ada berbagai macam tambang di sana, yang dikelola oleh asing, berada di Papua juga. Mereka concern dengan apa yang terjadi,” tutur Achmad.
Mengutip dari Anthony Giddens (Runaway World, 1996) bahwa demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan global semakin meningkat di awal abad ke-21, menjadikan Papua lanskap yang terbuka. Apa yang terjadi di Papua dapat diketahui langsung oleh dunia.
Perubahan masif juga mengubah pandangan yang bersifat etik menjadi pandangan emik, yakni memandang papua dari sudut pandang orang Papua sendiri. Representasi Papua yang sebelumnya adalah homogenitas telah bergeser menjadi heterogenitas.
Pandangan positivisme yang lahir seiring dengan perubahan yang terjadi juga menggeser posisi manusia dari obyek menjadi subyek (subyektivikasi).
Hal ini mendorong meningkatnya kebebasan individu, atomisasi individu, pembentukan elit-elit baru, meningkakatnya politik kebudayaan, dan aktor (pemerintah, partai politik, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, lembaga donor dari luar negeri, pemerintah asing, dan institusi masyarakat lokal) menjadi sentral.
Adapun hal-hal yang harus diperbaiki dari menyoal Pembangunan Papua melalui kacamata sosial budaya yang terjadi antara lain; kemajemukan kebudayaan yang dipandang sebagai anugerah sekaligus kerentanan.
Juga relativisme kebudayaan atas nama demokrasi dan HAM yang justru mempertajam batas-batas sosial budaya, penafsiran kebebasan yang berlebihan, dan lemahnya kontrol atas kebebasan individu dan kelompok. (sak)